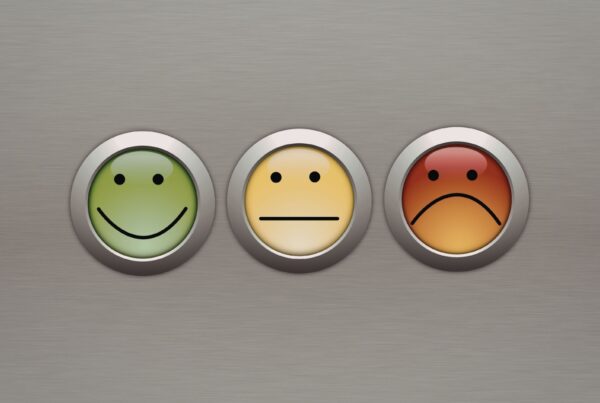Ego, secara sederhana dialihbahasakan sebagai “keakuan”. Ini adalah konsepsi tentang Sang Diri sebagai individu yang terpisah dari individu lainnya, dengan karakter pribadi yang unik. Saat Sang Suwung memanifestasi menjadi segala yang ada, termasuk memanifestasi sebagai manusia – keberadaan ego menjadi satu keniscayaan. Setiap jiwa sebagai manifestasi dari Sang Suwung pada dasarnya pasti menyadari keberbedaan dan keunikan dibandingkan dengan pribadi yang lain. Inilah kenyataan pada dimensi keragaman: pada titik ini Hyang Wisnu berbeda dengan Hyang Siwa. Tom Cruise berbeda dengan Kasino, dan kita semua saling berbeda.
Menimbang itu semua, adanya ego merupakan kewajaran. Dalam konteks laku spiritual pun sebenarnya keberadaan ego ini merupakan satu kenyataan yang sewajarnya diterima. Atas dasar kesadaran adanya ego atau individu yang saling terpisah inilah kita lalu bisa memaklumi proses dan tataran evolusi jiwa yang berbeda-beda.
Lalu, mengapa ada ujaran spiritual tentang penyirnaan ego? Ini perlu kita mengerti dengan tepat. Yang dimaksud adalah seyogyanya setiap pejalan tidak melekat terlalu kuat dengan konsepsi keterpisahan ini. Kita perlu beranjak untuk menyadari bahwa pada dasarnya kita satu dan bersumber pada Realitas Tunggal yang meliputi seluruh keberadaan. Saat kita menyelam ke dalam diri memang pastilah dijumpai satu dimensi realitas dimana tak ada yang berbeda dari satu pribadi ke pribadi lainnya, bahwa esensi dari semua jiwa adalah Sang Hyang Atman/Roh Kudus yang sama.
Pada keadaan diri kita berkesadaran utuh, kita akan menjadi tahu bahwa keterpisahan dan kesatuan adalah sama-sama kebenaran, keduanya adalah realitas hanya berasa pada tataran yang berbeda. Secara faktual tak ada yang harus disangkal. Jadi, ujaran penyirnaan ego tak harus dimaknai secara harfiah. Karena pada kenyataannya juga tak ada ego yang bisa disirnakan. Setiap orang tercerahkan tetap punya ego dalam pengertian tetap punya keunikan pribadi, punya karakter berbeda dari orang tercerahkan lainnya.
Berikutnya, yang sebenarnya perlu diatasi adalah egoisme atau watak egoistik. Ini adalah tentang kecenderungan mementingkan diri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Kecenderungan dan watak ini muncul pada jiwa-jiwa yang kurang terhubung kepada Sang Hyang Atman/Roh Kudusnya, sehingga kurang diliputi Kasih Murni.
Berdasarkan uraian di atas, maka tak mungkin juga ada guru spiritual atau penulis spiritual yang tiada punya ego. Nyatanya masing-masing tetap merasa sebagai pribadi yang terpisah dan berbeda. Seperti saya, menulis buku ya tetap saya kasih nama penulis SHD. Saya juga tidak akan mau dipanggil dengan nama yang bukan nama saya. Yang membedakan kualitas spiritual dan tingkat kesadaran seorang guru spiritual maupun pembelajar spiritual, bukanlah soal ada tidaknya ego karena itu pastilah ada. Tetapi adalah sejauh mana watak welas asih memenuhi dirinya, sejauh mana diri selalu dituntun oleh Sang Hyang Atman/Roh Kudus, dan sejauh mana tindakannya selalu ada dalam koridor pelayanan yang otentik bukan manipulatif.
Lebih lanjut perlu dimengerti saat seorang guru spiritual dengan kesadaran penuh menguraikan mana kenyataan dan mana ilusi, termasuk memberi umpan balik tentang apa yang terjadi pada seorang pembelajar – apakah berada dalam jalur pencerahan atau membelokkan diri dari pencerahan, maka itu bukanlah tindakan egoistik. Itu adalah realisasi kasih dan kepedulian. Akan sangat tidak patut jika seorang guru spiritual asyik dengan hening dan keselamatan pribadinya, tanpa peduli pada keselamatan orang lain, termasuk orang-orang yang ada dalam bimbingannya.
Rahayu.
Setyo Hajar Dewantoro
Reaksi Anda: